
Dari Putri Marino Sampai Dangdut Koplo, Kita Adalah Juri di Jagat Maya
Sosial media adalah topeng bagi siapapun yang memakainya, lewat sederet kalimat sumpah serapah dibalik akun palsunya.
Beberapa waktu lalu jagat maya sempat ramai dengan segala macam komentar tentang perilisan buku puisi Putri Marino. Seorang aktris yang sempat memenangkan Piala Citra untuk perannya di film ‘Posesif’. Satu hal yang mereka sepakati jika puisi-puisi Putri dibuku tersebut kurang layak dirilis. Dikerucutkan pada apa yang tertulis di linimasa si burung biru, kebanyakan dari mereka menjadi ‘juri’ tentang puisi Putri. Mereka, dengan segala macam estetika seni yang mereka yakini berpendapat jika tulisan Putri tidak bisa dimaafkan, dan menyarankan Putri main film saja.
Lepas dari itu, Putri mungkin ketiban sial, karena sebelumnya tren penulisan buku puisi cukup ramai dirilis, dengan semua kebanalannya. Namun karena beberapa diantaranya punya 'nama' duluan membuat banyak penerbit membuka pintu lebar untuk merilisnya. Kekesalan para pembaca yang berseberangan dengan tren itu akhirnya seperti mendapati puncaknya saat Putri merilis buku puisi. Sama seperti penulis lainnya yang punya ‘nama’ duluan sebelum rilis buku, Putri dianggap aji mumpung saja, sampai akhirnya ada penerbit yang tertarik merilis bukunya. Tidak salah jika konteksnya bisnis. Namun ketika kemudian jadi sebuah formula dari “tips agar buku laku di pasaran”, maka itu yang kemudian menimbulkan reaksi di atas.
Hal tersebut terjadi juga di ranah musik tanah air, dari mulai tren lagu melayu sampai hari ini ketika remaja menggandrungi musik koplo, yang menurut banyak pemerhati musik kurang layak memenuhi ‘standar estetika’ seni yang ‘seharusnya’. Sialnya, penilaian tersebut berbanding terbalik dengan torehan kesuksesan para musisinya, dan para ‘kritikus’ tersebut dianggap sebagai angin lalu saja. Benar jika industri musik akan lebih hidup jika ada kritik di dalamnya (selama itu bisa dipertanggung jawabkan dengan argumen yang valid), sehingga membuat dinamika industri semakin bergairah. Namun jika yang menilai hanya berlandaskan pada perspectif yang kurang bisa dipertanggung jawabkan, apakah kritik tersebut tidak akan sama-sama menjadi banal?
Bicara tentang kritik, sebuah grup musik Sungsang Lebam Telak pernah begitu terganggu dengan citra musik jazz yang seakan mengeksklusifkan diri dibanding genre musik lainnya. Dianggap pretensius atau jadi ajang pencitraan semata, karena kebanyakan hanya disajikan di tempat-tempat 'mahal', hingga memunculkan asumsi yang menyukai musik ini mendapat legitimasi dengan predikat ‘yang paling ngerti musik’. Tidak semuanya memang, tapi mungkin yang bersentuhan dengan Sungsang Lebam Telak seperti itu. Outputnya, mereka kemudian memainkan genre musik yang mereka namakan free jazz/superjazz noise kontemporer, dengan permainan musik dan penulisan judul lagu absurd, serta cenderung nihilis. Mereka seperti sedang 'mengejek' dengan ekslusivitas tersebut. Mereka bermain jazz di tempat/club kecil, gratis, dan disajikan dengan permainan 'nihilis' itu tadi. Menyenangkan, jika kalian juga termasuk orang-orang yang menempatkan gaya nihilis sebagai estetika seni yang menarik.
Sungsang Lebam Telak tidak sendiri karena di genre lain, sebutlah musik rock, ada Teenage Death Star yang juga menempatkan gaya nihilis di pola kreasi musik mereka. Uniknya, baik itu Sungsang Lebam Telak atau pun Teenage Death Star luput dari kritik para ‘kritikus musik’ seperti yang disebutkan di atas. Sungsang Lebam Telak malah diganjar penghargaan bergengsi Indonesian Cutting Edge Music Award (ICEMA), kategori ‘Best Noise/Experimental Song’, untuk lagu “Semburan Diare Langsung ke Lidah yang Telah Terpatahkan oleh Teori Usang Tata-Titi Bersepeda”. Sedangkan Teenage Death Star dianggap sebagai ‘nabi’ bagi generasi hari ini untuk urusan aksi panggung ugal-ugalannya. Menjadi standar untuk band-band setelahnya yang ingin membangun citra urakan namun ‘artsy’. Sayangnya, kebanyakan dari mereka gagal.
Kembali ke bahasan soal ‘kita adalah juri di jagat maya’. Hal tersebut bisa dibilang menjadi sejalan dengan kutipan yang mengatakan “berilah seseorang topeng, maka dia akan menjadi dirinya yang sebenarnya”. Sosial media adalah topeng bagi siapapun yang memakainya, lewat sederet kalimat sumpah serapah dibalik akun palsunya. Padahal di dunia nyata, mungkin dia kerap berlaku lembut dengan tutur halus di setiap perkataannya. Menjadi gemar menghakimi karena topeng yang dipakainya, dan mungkin itu pula yang menimpa Putri Marino dan dangdut koplo, ketika kehadirannya dianggap tidak layak oleh sebagian orang yang merasa lebih tahu tentang estetika karya yang ideal menurut mereka.
‘kita adalah juri di jagat maya’, karena di dunia nyata kebanyakan dari kita tidak punya nyali untuk berkomentar sepedas di instagram misalnya. Karena di dunia nyata kita meletakan topeng kita dan ketakutan akan citra yang akan disematkan orang pada kita. Lalu bersembunyi di balik akun sosial media, dan menemukan kebebasan bersuara. Terlalu bebas, hingga yang terburuk, mampu memicu seseorang melakukan tindakan bunuh diri karena rundungan di sosial media. Putri Marino saya yakin tidak akan seperti itu, begitu juga Feel Koplo. Semoga saja.
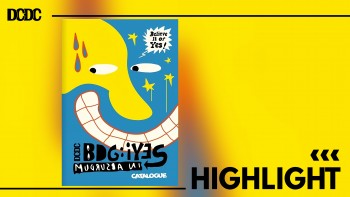














Comments (0)